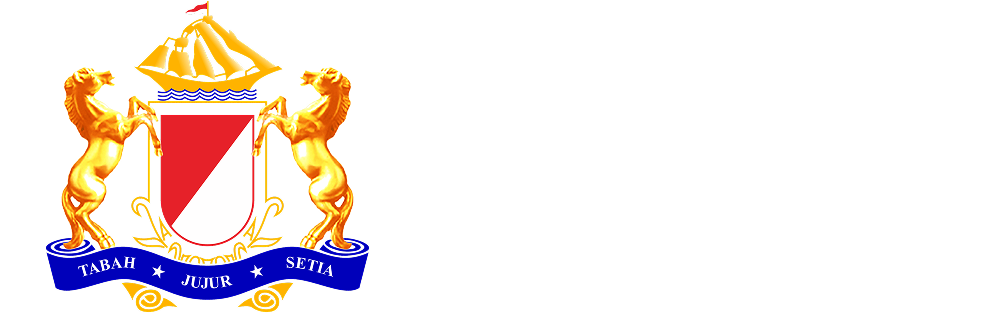Keputusan Israel untuk menyerang Iran pada 13 Juni 2025 tampak bertentangan dengan momentum diplomatik, mengingat pada 15 Juni AS dan Iran dijadwalkan memulai perundingan nuklir. Namun bagi Israel, situasi ini justru dianggap sebagai peluang strategis: Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, dan rezim Bashar Assad di Suriah tengah melemah. Israel khawatir jika kesepakatan Iran–AS tercapai, hal itu hanya akan memberi Iran waktu untuk konsolidasi internal dan memperkuat posisinya di kawasan.
Amerika kemudian melihat peluang serupa, pada 22 Juni, Presiden Trump memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas pengayaan uranium Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, dengan tujuan menghentikan program senjata nuklir Iran dan mendorong Teheran kembali ke meja perundingan. Tentu saja sulit bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan, setelah dipermalukan oleh Israel dan Amerika.
Target selanjutnya bagi Israel adalah Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, dengan harapan mengguncang rezim dan mendorong transisi kekuasaan. Namun, AS tampak enggan mendukung opsi ini, karena pembunuhan tokoh religius dapat memicu reaksi keras, tidak hanya dari komunitas Syiah di Irak, Lebanon, dan Suriah, tetapi juga dari negara-negara non-Syiah yang menolak kekerasan terhadap figur keagamaan. Pertanyaannya: apakah AS memiliki cukup pengaruh untuk menahan Israel dari mengeksekusi Khamenei?
Apa yang Iran akan lakukan? Beberapa saat setelah serangan Amerika, Iran melanjutkan serangan rudal ke Israel. Alih-alih melemahkan Iran, serangan AS justru mengonsolidasikan dukungan dari kelompok nasionalis dan garis keras yang merasa dipermalukan oleh tindakan Amerika dan Israel. Namun, faksi moderat di Iran tetap berhati-hati, khususnya dalam merespons terhadap aset-aset militer AS di kawasan.
Meski pembalasan tampak tak terelakkan, sejumlah faksi Iran berupaya menahan diri agar konflik tidak meluas dan menyeret AS lebih jauh. Konsolidasi internal di Iran kemungkinan akan berlangsung dalam waktu dekat, dan respons yang muncul akan sangat menentukan arah eskalasi. Pilihan seperti menutup Selat Hormuz atau Laut Merah dapat memicu lonjakan harga energi global dan merugikan banyak negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik—risiko yang disadari Iran, karena dapat menggerus simpati internasional terhadap mereka.
China, Qatar, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengumukan kekhwatiran mereka atas serangan Amerika ke Iran, dan khawatir mengenai potensi meluasnya perang.
Risiko Politik dan Ekonomi
Perang ini menimbulkan dua risiko utama. Pertama, potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran—jalur vital bagi logistik minyak dan bahan kimia global—dapat memicu lonjakan harga energi, terutama minyak, secara drastis. Kedua, konflik yang meluas ke wilayah lain di Timur Tengah dapat mengganggu jalur logistik internasional dan memperparah ketidakpastian ekonomi global.
Bagi Indonesia, eskalasi konflik ini berpotensi menahan ekspansi sejumlah perusahaan, karena konsumsi global kemungkinan akan melambat. Namun, di sisi lain, permintaan terhadap bahan tambang—terutama untuk produksi stainless steel dan alat pertahanan—diperkirakan meningkat, seiring naiknya pesanan senjata dan perlengkapan militer selama konflik berlangsung.
Di sisi industri, kenaikan biaya-biaya terkait dengan logistik dan energi bisa memberikan tekanan untuk industri seperti seemen baja dan petrokimia. Di sisi lain, tekanan sektor Keuangan seperti pelemahan rupiah harus menjadi perhatian, dan tentunya ketidakpastian yang tinggi bisa menunda prospek penurunan suku bunga Bank Indonesia.
Posisi Amerika Serikat
Presiden Trump menghadapi tekanan domestik di tengah kekhawatiran publik bahwa AS akan terseret ke dalam konflik Israel-Iran. Tokoh konservatif seperti Tucker Carlson telah memperingatkan agar AS tidak terlibat langsung. Namun, seperti dicatat oleh Thomas L. Friedman, kebijakan Trump sebelumnya—termasuk keluar dari JCPOA dan strategi “tekanan maksimum”—telah melemahkan posisi diplomatik AS dan mendorong Israel bertindak unilateral. Eskalasi ini berdampak pada Indonesia, terutama dalam ketahanan energi, stabilitas perdagangan global, dan posisi diplomatik di tengah tatanan dunia yang semakin terfragmentasi.
Dukungan bipartisan terhadap Israel di Kongres dan dalam politik Amerika secara umum tetap sangat kuat, terutama dalam hal kerja sama pertahanan dan intelijen. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa faksi anti-perang dari Partai Demokrat progresif dan Partai Republik non-intervensionis mulai semakin vokal dalam menolak keterlibatan militer lebih lanjut. Sejumlah anggota Kongres menyerukan agar pemerintahan AS menahan diri dan mendorong de-eskalasi konflik, mengingat risiko perang regional yang lebih luas. Menurut laporan Associated Press,
Kongres saat ini tengah menghadapi tekanan domestik yang meningkat untuk menyeimbangkan dukungan terhadap Israel dengan upaya mencegah keterlibatan AS dalam konflik terbuka. Selain itu, survei Pew Research yang dilakukan pada 24–30 Maret menunjukkan bahwa lebih dari 53% masyarakat dewasa di AS kini memiliki persepsi yang kurang positif terhadap Israel, meningkat dari 42% pada tahun 2022.
Sementara itu, situasi domestik di AS semakin memanas, menyusul aksi unjuk rasa anti-ICE di Los Angeles yang kini telah menyebar ke kota-kota besar di Pantai Timur, seperti New York, Boston dan Philadelphia. Serangan ke Iran bisa memperburuk reputasi domestik Trump, atau digunakan Trump untuk mengkonsolidasikan faksi-faksi domestik.
Posisi Tiongkok
Mengingat Rusia tersedot dalam perang dengan Ukraina. Tiongkok merupakan satu-satunya sekutu Iran yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang masih signifikan. Namun, Beijing akan bersikap sangat hati-hati. Tiongkok tidak ingin pasokan minyak dari Iran terganggu karena Iran terlalu fokus mengalokasikan sumber dayanya untuk perang. Meski kemungkinan besar akan memberikan dukungan kepada Iran, Tiongkok akan melakukannya secara tertutup dan strategis, dengan tetap menjaga stabilitas pasokan energi dan hubungan dagang global.
Figur yang kita perlu tahu?
Tangan kanan Presiden Trump, Steve Witkoff? Trump dan Witkoff pertama kali bertemu pada tahun 1980-an, ketika Witkoff baru memulai kariernya sebagai pengacara properti. Trump mendorongnya untuk terjun ke dunia bisnis real estat, yang kemudian diwujudkan Witkoff dengan mendirikan perusahaannya, Witkoff Group, pada awal 1990-an. Perusahaan ini memiliki sejumlah properti bergengsi di New York, termasuk Hotel Park Lane dan Gedung Woolworth.
Trump kemudian menunjuk Witkoff sebagai utusan khusus untuk berbagai misi diplomatik, termasuk negosiasi di Gaza dan Ukraina. Penunjukan ini didorong oleh ketidakpercayaan Trump terhadap para diplomat senior di Departemen Luar Negeri yang ia anggap terlalu “hawkish” dan kurang mengutamakan pendekatan diplomatik. Trump juga melihat Witkoff sebagai loyalis yang setia dan dapat diandalkan untuk menjalankan visinya.
Ketika Trump memecat Mike Walsh dari posisi National Security Advisor (NSA) atau setara dengan Menkopolhukam, muncul spekulasi bahwa Witkoff akan menggantikan Walsh, terutama karena jabatan NSA tidak memerlukan persetujuan Senat. Namun, rencana tersebut tertunda setelah pecahnya perang antara Iran dan Israel, serta karena Rusia tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti arah diplomasi yang diupayakan Trump dan Witkoff.
Pecahnya hubungan antara Elon Musk dan Trump justru membuat Trump semakin mengandalkan loyalis lamanya, ketimbang figur-figur baru yang belakangan masuk ke dalam lingkarannya. Dalam konteks ini, posisi Steve Witkoff tetap strategis—baik dalam urusan hubungan luar negeri maupun sebagai perantara (broker) antara berbagai pihak yang ingin menjalin komunikasi dengan Trump.