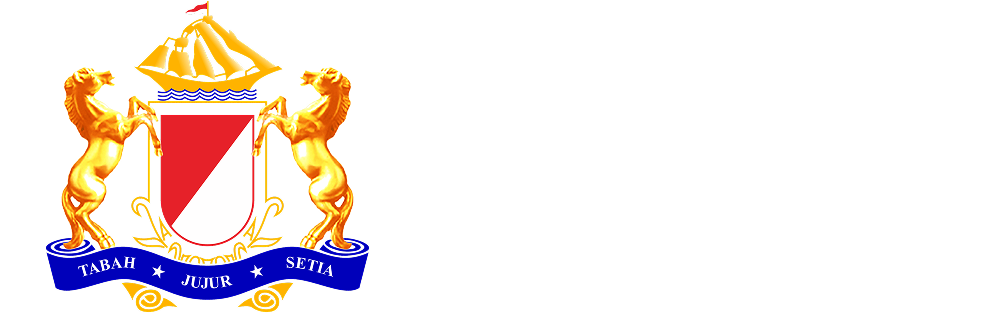Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia siap menerima investasi Amerika Serikat di sektor mineral kritis. Ia menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa, namun pernyataan ini jelas merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dagang Indonesia–AS yang ditekan pada 22 Juli 2025.
Pembahasan mengenai akses dan investasi AS di sektor mineral kritis bukan hal baru. Saat menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pernah membahas peluang insentif dari Inflation Reduction Act dan CHIPS and Science Act yang memerlukan pasokan material tambang termasuk mineral kritis. Pada Juli 2025, Airlangga Hartarto mengumumkan kesepahaman lanjutan dengan AS mencakup tarif, hambatan non-tarif, dan potensi investasi US$34 miliar.
Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa setelah bertahun-tahun, investasi baru perusahaan tambang AS di Indonesia belum terlihat? Hingga kini, Freeport-McMoRan masih menjadi pemain utama, bahkan mungkin satu-satunya, perusahaan tambang AS di Indonesia—berbeda dengan Tiongkok yang memiliki lebih dari 20 perusahaan aktif. Padahal, laporan CSIS Washington DC mencatat lembaga seperti Defense Logistics Agency (DLA) memerlukan pasokan besar mineral kritis seperti tembaga, nikel, timah, dan aluminium, komoditas unggulan Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Situasi ini menambah keheranan mengapa perusahaan AS belum berbondong-bondong mengamankan aset mineral kritis di Indonesia.
Hal lain yang juga menambah pertanyaan adalah Amerika sendiri cukup khawatir terhadap dominasi investor China di sektor pertambangan Indonesia. Dalam berbagai pertemuan, pihak Amerika secara terbuka menyampaikan kekhawatiran ini. Tentu saja, hal ini menjadi alasan tambahan bagi Amerika untuk berupaya mengurangi dominasi China di sektor mineral kritis di Indonesia.
Menurut kami, ada dua faktor utama yang membuat investasi AS di sektor ini berjalan lambat:
- Identifikasi aset belum matang
Banyak lokasi tambang di Indonesia belum mencapai tahap identifikasi penuh (full identification). Masih diperlukan eksplorasi tambahan untuk memastikan kandungan mineral, jumlah dan karakteristik cadangan, serta kondisi kontur lokasi yang akan mempengaruhi kelayakan ekonominya.
Sebagai contoh, pada aset tembaga yang terindikasi di Sumbawa, eksplorasi lanjutan diperlukan untuk mengkonfirmasi cadangan terbukti, menentukan apakah metode penambangan yang sesuai adalah underground mining atau open pit, serta merancang jenis pengelolaan limbah yang dapat diterapkan berdasarkan kondisi kontur wilayah. - Tingginya non-operational cost
Ketidakpastian kontrak dan risiko politik di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain tempat perusahaan Amerika Serikat beroperasi, seperti Chile, Peru, Meksiko, Kanada, atau Australia. Di antara berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investasi, risiko regulasi menjadi pertimbangan terbesar bagi banyak perusahaan AS.
Kedua masalah ini bersifat berbeda: yang pertama bersifat teknis dan terkait biaya operasional, sedangkan yang kedua bersifat non-teknis atau politis. Perlu dipahami, masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia atau hanya dihadapi investor AS. Investor dari negara lain, termasuk Tiongkok, juga menghadapi tantangan regulasi dan politik di Indonesia.
Namun, perusahaan AS memiliki satu kendala tambahan: aturan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Undang-undang ini memungkinkan perusahaan dan pegawainya dituntut di AS jika terlibat praktik yang dianggap korupsi atau tidak pantas menurut standar hukum AS di negara tempat mereka berinvestasi. Konsekuensinya, perusahaan AS sangat berhati-hati berinvestasi di sektor dengan risiko tinggi seperti pertambangan.
Salah satu solusi adalah membentuk One-Stop Mineral Kritis Desk, lembaga yang menangani perizinan sekaligus menawarkan skema risk sharing untuk eksplorasi, terinspirasi model kontrak cost recovery di sektor migas yang sukses menarik investasi besar dari Chevron, ExxonMobil, BP, ENI, dan TotalEnergies selama enam dekade. Model ini dapat mengurangi risiko, mengundang investor asing non-Tiongkok, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan mendiversifikasi mitra strategis.
Dengan mengurangi risiko melalui mekanisme yang terukur dan dikelola oleh satu otoritas, kebijakan ini tidak hanya akan menarik investor asing, tetapi juga menguntungkan investor domestik. Dampaknya bersifat strategis: menciptakan persaingan sehat antar investor, memperkaya variasi kepemilikan aset, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan mendiversifikasi mitra dalam pengelolaan sumber daya kritis.
Jika pemerintah ingin mewujudkan investasi mineral kritis dari AS, kuncinya adalah mengurangi hambatan teknis dan non-teknis melalui kebijakan yang transparan, efisien, dan meminimalkan risiko bagi investor.