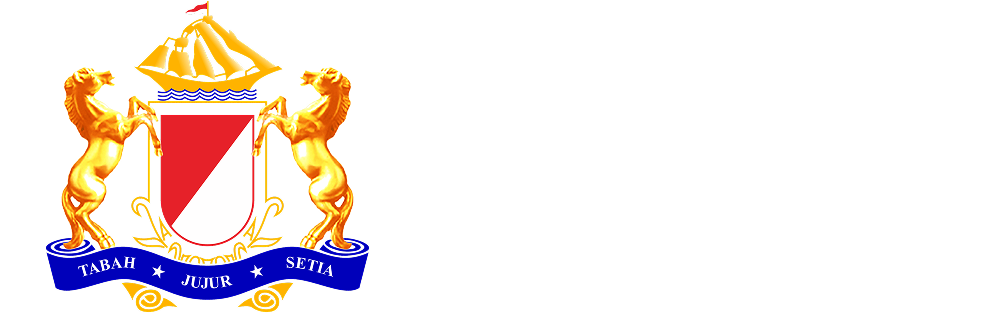Pada 7 Juli 2025, Presiden Trump mengirimkan surat resmi yang menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap Indonesia, berlaku mulai 1 Agustus 2025. Tarif ini adalah perpanjangan dari tarif pada Liberation day di 2 April 2025. Pada tarif baru ini, negara Asia Tenggara lain juga terdampak: Malaysia (25%), Thailand (36%), Laos (40%), dan Kamboja (36%).
Keputusan ini mengejutkan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengajukan proposal resmi pada bulan Mei yang mendapat respons positif oleh Jamieson Greer dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat), yang mengapresiasi inisiatif Indonesia. Namun, Presiden Trump justru membalas dengan surat baru berisi penetapan tarif dan perpanjangan tenggat waktu hingga awal Agustus.
Saat surat itu diterbitkan, Presiden Prabowo sedang menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Trump juga mengancam tarif tambahan 10% untuk negara BRICS. Menko Airlangga segera dikirim ke Washington untuk negosiasi. Pada 9 Juli, Menko Airlangga bertemu dengan Secretary of Commerce Howard Lutnick dan USTR Jamieson Greer. Dari pertemuan itu, Menko Airlangga mengumumkan dua hal penting:
1. Penerapan tarif 32% ditunda selama proses negosiasi berlangsung, bahkan jika melewati tenggat 1 Agustus.
2. Indonesia tidak akan dikenai tambahan tarif 10% sebagai anggota BRICS.
Namun, kedua janji tersebut tetap harus disikapi dengan hati-hati mengingat karakter kebijakan Presiden Trump yang mudah berubah.
Dalam suratnya, Trump membuka peluang penghapusan tarif jika Indonesia mengurangi hambatan dagang, berinvestasi di sektor manufaktur AS, atau memindahkan basis produksi ke Amerika—syarat terakhir sulit dipenuhi karena tingginya biaya investasi dengan keuntungan belum tentu optimal, serta kebutuhan domestik yang besar akan basis produksi untuk penyerapan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia mungkin mempertimbangkan Danantara sebagai kendaraan investasi di AS, namun pendekatan ini perlu perhitungan matang.
Belajar dari Vietnam: Strategi Menghadapi Tekanan Tarif Presiden Trump
Sebelum mempertimbangkan pemenuhan permintaan Presiden Trump, Indonesia sebaiknya bercermin pada negara yang relatif berhasil menghadapi tekanan serupa, yaitu Vietnam.
Vietnam menjadi negara kedua setelah Inggris yang berhasil mencapai kesepakatan dagang bilateral dengan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Presiden Trump tetap menerapkan tarif 20% terhadap Vietnam, angka ini memang lebih rendah dibandingkan tarif awal 46%.
Pemerintah Vietnam menyadari bahwa kesepakatan terbaik yang bisa mereka harapkan adalah pengurangan tarif, bukan penghapusan total.
Menariknya, Vietnam tidak menempuh jalur investasi langsung di Amerika untuk meraih kesepakatan. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan informal dan simbolik, seperti:
1. Memberikan insentif terhadap proyek Trump International Golf and Hotel di Hung Yen.
2. Melakukan pembelian LNG dan pesawat buatan AS—strategi yang juga diajukan oleh Indonesia namun belum membuahkan hasil.
Apa Strategi Vietnam?
Salah satu jawabannya terletak pada infrastruktur diplomatik yang aktif dan terkoordinasi di Vietnam. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nguyen Hong Dien memimpin langsung proses negosiasi, didukung oleh duta besar yang aktif memantau dan membangun komunikasi intensif di Washington, D.C. Sebaliknya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki duta besar aktif yang menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
Kami berpendapat bahwa tidaknya aktifnya jalur diplomasi Indonesia di Washington, termasuk lemahnya tindak lanjut terhadap proposal yang telah disampaikan, merupakan penyebab utama gagalnya negosiasi tarif Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan investasi di Amerika, sebagaimana yang juga tidak dilakukan oleh Vietnam dan Inggris. Yang dibutuhkan adalah 1. Pertemuan dengan pemangku kepentingan yang tepat di AS; 2. Komitmen negosiasi yang konsisten; dan 3. Jalur komunikasi diplomatik yang aktif dan berkelanjutan.
Dampak dari negosiasi tarif untuk Indonesia?
Apa yang disampaikan Presiden Trump dalam suratnya tentu perlu dicermati dan ditanggapi dengan serius. Namun, dalam menghadapi Trump, yang lebih penting adalah membaca hal-hal yang tidak tertulis.
Permintaan agar Indonesia berinvestasi di AS justru berkontradiksi dengan agenda penguatan industri dalam negeri dan berisiko mengalihkan sumber daya dari kebutuhan domestik. Lebih lagi, Vietnam yang berhasil mendapat pengurangan tarif tanpa investasi di AS, sementara Jepang tetap dikenai tarif 25% meski telah berinvestasi melalui SoftBank. Ini menunjukkan bahwa investasi bukan jaminan keberhasilan negosiasi.
Pendekatan strategis dan personal lebih efektif, seperti memanfaatkan potensi kepentingan bisnis Trump di Indonesia—misalnya proyek Trump Residence dan Trump International Golf di Lido —sebagai bagian dari daya tawar, dikombinasikan dengan rencana pembelian produk AS, dan/atau tawaran berinvestasi di mineral kritis di Indonesia.
Proposal Indonesia, termasuk yang disusun KADIN, harus melibatkan “agenda tidak tertulis” Trump tanpa mengorbankan integritas dan kepentingan nasional.
Pada edisi minggu depan, kami akan membahas lebih dalam peran mineral kritis yang berpotensi menjadi alat tawar dalam hubungan geo-ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia, mengingat Departemen Pertahanan AS cukup agresif dalam mengamankan pasokan mineral tersebut